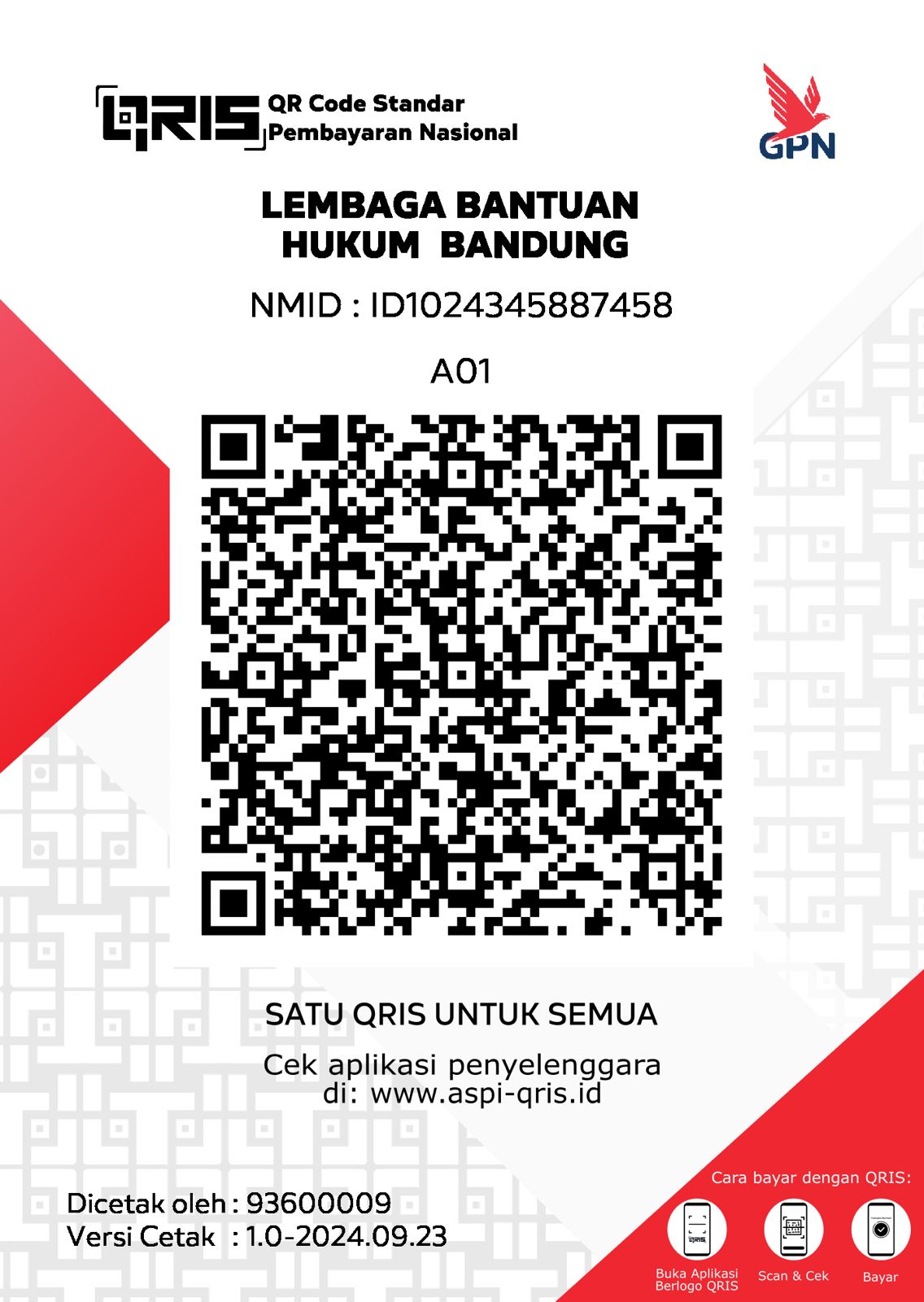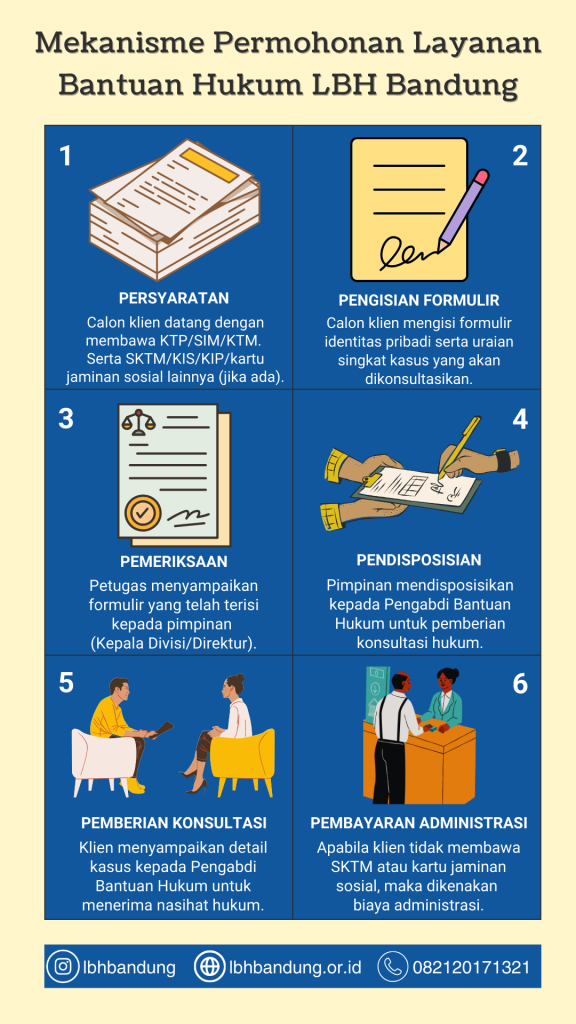

Kontruksi Hukum Pasal 1 UUD 1945 dan Republikanisme: Sebuah Refleksi Pasca Reformasi.
Pasal 1 UUD 1945
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
Jika kita refleksikan pasal 1 UUD 1945 itu bisa kita lihat bahwa negara Indonesia itu adalah republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan Negara kita adalah negara hukum. Dari bunyi pasal tersebut mari kita refleksikan dan berpikir kembali untuk menelaah lebih dalam pemaknaan tersebut. Jika kita lihat bunyi pasal tersebut dibuat dalam beberapa ayat namun berada dalam 1 nafas pasal yang sama, yang berarti memang bunyi kalimat tersebut adalah sebuah hal yang saling berkaitan erat dan tidak bisa terpisahkan baik itu mengenai republik, kedaulatan rakyat, serta negara hukum (rule of law). Sebelum membahas itu mari kita awali refleksi tersebut dengan kondisi negara saat ini.
Kondisi negara saat ini dengan sejarah yang panjang sudah menorehkan sebuah cerita bangsa yang memilukan. Cerita tersebut mari kita tarik pasca reformasi bagaimana semangat reformasi yang menumbangkan orde baru justru lahir dalam keadaan prematur dimana amanat reformasi terkait enam tuntutan yaitu penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan mantan presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri), dan terakhir pemberian otonomi daerah seluas-luasnya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh bangsa ini.
Jika berbicara penegakan supremasi hukum jelas nilai negara ini mendapatkan nilai 11 dari 100, kita tahu bagaimana hukum dijadikan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan dan untuk kepentingan keluarganya bercermin dari Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu, hukum dijadikan alat legitimasi dan justifikasi lewat Program Strategis Nasional (PSN) yang menimbulkan konflik agraria dengan rakyat dan memuluskan bisnis para oligarki. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2020-2023, ada 115 letusan konflik agraria akibat PSN. Luas lahan dan jumlah korban terdampak masing-masing 516.409 ha dan 85.555 keluarga.
Berbicara pemberantasan KKN apa yang seharusnya dicitakan justru semakin mundur mengingat pada tahun 2019 lembaga KPK yang secara historis seharusnya berdiri secara independen sebagai respon atas ketidakpercayaan publik terhadap institusi kejaksaan dan polisi. Namun kewenangannya dipangkas oleh revisi Undang-Undang (UU) KPK melalui UU No. 19/2019, yang pada akhirnya status KPK tak lagi independen melainkan berada di bawah rumpun eksekutif dan status pegawainya yang beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Lalu, mengenai tuntutan atas pengadilan mantan presiden Soeharto dan kroninya hanyalah angan-angan reformasi yang tidak pernah terlaksana. Lewat studi dari Richard and Vedi R. Hadiz “Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy In An Age of Markets” (2004) menelusuri kemunculan model pemerintahan oligarkis di Indonesia semenjak pemerintahan Soeharto dengan Orde Baru-nya dari tahun 1965-1997. Dalam analisis Robison dan Hadiz, rezim oligarkis era reformasi berhasil mengkonsolidasikan dirinya setelah jatuhnya Soeharto. Meskipun pada awalnya para konglomerat dan kelompok politik-bisnis lama perlahan mundur ke belakang. Dalam situasi ini, mereka tidak lagi bisa mengandalkan rezim otoriterian-sentralistis untuk melindungi kepentingan mereka dan juga memperoleh dispensasi atas hutang-hutang mereka. Kelompok-kelompok ini yang kemudian bertransformasi menjadi predator baru, menggantikan rezim predator Soeharto. Kelompok bisnis-politik ini mulai menguasai sentra-sentra pemerintahan dan legislatif, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, yakni provinsi dan kabupaten/kota.
Berbicara ditingkat lokal seperti provinsi dan kabupaten yang berarti berbicara soal pemberian otonomi daerah seluas-luasnya sesuai amanat reformasi nyatanya pun jika kita refleksikan tak ada bedanya dengan “hantu-hantu orba” jika pemerintah daerah hanyalah perpanjangan kekuasaan dari pusat serta para oligarki. Hal ini tercermin ketika baik pusat dan daerah ketika setiap datangnya pemilu/pemilukada dalam setiap kampanye atau orasi publiknya selalu menjanjikan kemakmuran, kesejahteraan dan kesamaan bagi rakyat. Dari sinilah mungkin logika kedaulatan rakyat menempati posisi pemerintah berdaulat negara yang membawanya untuk pertama-tama mempertahankan kedaulatannya dengan aktif mengkomodifikasi gagasan-gasasan universal dan menjualnya kepada rakyat untuk kemudian ditukar dengan kepatuhan dan legitimasi. Sehingga kedaulatan rakyat hanyalah sumber penopang legitimasi pemerintah.
Maka dari itu jika kedaulatan rakyat adalah inti dari negara atau fitur utama negara, maka republikanisme adalah kedaulatan in action. Sebagaimana dalam buku Robertus Robert Republikanisme: Filsafat Politik Untuk Indonesia (2021) perlu diketahui jika republikanisme memiliki sejumlah perspektif dan preposisi yaitu pertama: preposisi mengenai kebaikan bersama (common good), Kedua civic virtue (keterlibatan aktif warga untuk mencapai keutamaan dan membela kebebasannya, Ketiga peran partisipasi warga. Keempat, sikap kewargaan yang aktif. Preposisi kelima adalah patriotisme dalam arti keberanian memperjuangkan common good atau kebaikan bersama tadi.
Dari preposisi tersebut, maka yang menjadi pertanyaannya adalah bukankah peristiwa-peristiwa memilukan tersebut terjadi karena tidak adanya partisipasi politik yang seluas-luasnya? Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi akibat negara mendominasi kebebasan atas rakyatnya yang menjadi objek yang didominasi? Bukankan ide republikanisme menekankan kebebasan sebagai non-dominasi, yang berarti tidak boleh ada kekuatan yang menindas atau mengendalikan individu maupun kelompok tanpa legitimasi? Jika republik adalah orientasi pemerintahan yang membuka partisipasi politik luas maka sistem pemerintahan saat ini yang dapat memfasilitasi itu hanyalah demokrasi untuk saat ini. Mengenai demokrasi maka perlu kita refleksikan jika demokrasi tidak bisa lepas dari hukum dan begitu sebaliknya sesuai dengan teori rule of law. Sebagaimana Mahfud MD menyatakan “Demokrasi tanpa hukum akan menjadi liar dan anarkis, sedangkan hukum tanpa demokrasi adalah kezaliman”.
Berbicara negara hukum dan demokrasi tentu berbicara mengenai makna rule of law yang dimana menurut Brian Z. Tamanaha dalam bukunya “On the Rule of Law: History, Politics, Theory” (2004) membedakan wacana tentang negara hukum ini dalam dua kelompok teori. Ada teori-teori formal dan teori-teori substansial. Masing-masing kemudian dibedakannya menjadi tipis dan tebal. Atas dasar pembagian tersebut, lalu muncul enam varian negara hukum versi Tamanaha. Untuk negara hukum tipe formal yang paling tipis (thin) adalah rule-by-law. Pada konsep ini hukum dipakai sebagai alat oleh penguasa untuk menjamin ketertiban, dan ini lah yang paling disenangi oleh para penguasa. Berikutnya ada negara hukum legalitas formal (formal legality) yang memastikan ada hukum positif yang berlaku umum, jelas, dan prediktabel (berkepastian). Pada akhirya ada tipe negara hukum yang tebal (thick), yang menggabungkan demokrasi dan legalitas. Disinilah negara hukum yang tebal (thick) perlu diperjuangkan.
Dari refleksi atas peristiwa-peristiwa tersebut mulai dari pembusukan rule of law lewat putusan MK yang melanggengkan dinasti politik, pemaknaan rule by law oleh penguasa sehingga menimbulkan konflik agraria akibat kebijakan PSN, pelemahan KPK, pesta demokrasi yang sejatinya untuk kepentingan oligarki dan bukan rakyat, maka saya setuju atas pemikiran Hizkia Yosias lewat “Republikanisme, Hantu Kedaulatan, Dan Primasi Perlawanan Demokratis” (2011) yang menyatakan soal pendirian negara bahwa jika negara tidak pernah didirikan untuk rakyat, sedari mula ia didirikan atas aspirasi egois dari pemimpinnya (Paus/Kaisar/Raja/Pangeran/Presiden). Ironisnya, rakyat adalah kategori imajiner yang selalu diasumsikan, dan juga selalu dibawa-bawa untuk menjustifikasi pendirian negara sekaligus kekuasaan yang dinisbatkan kepada pemimpinannya.
Dari paparan yang sudah dijelaskan maka dalam kontruksi hukum pasal 1 UUD 1945 dan republikanisme memiliki banyak dimensi untuk direfleksikan baik itu dari soal negara republik, kedaulatan rakyat, negara hukum (thick) dan demokrasi. Kontruksi tersebut adalah suatu hal yang kompleks dan penting diingat oleh kita semua jika hal ini berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan kekuasaan negara membatasi kebebasan rakyatnya (negara mendominasi rakyatnya). Bahwa negara adalah suatu produk yang akan selalu membawa watak aslinya yaitu kekekalan kedaulatan bagi pemimpinnya semata, dan perlu disadari jika watak asli tersebut tidak akan pernah sesuai dengan gagasan demokrasi yang memfasilitasi ide republikanisme.