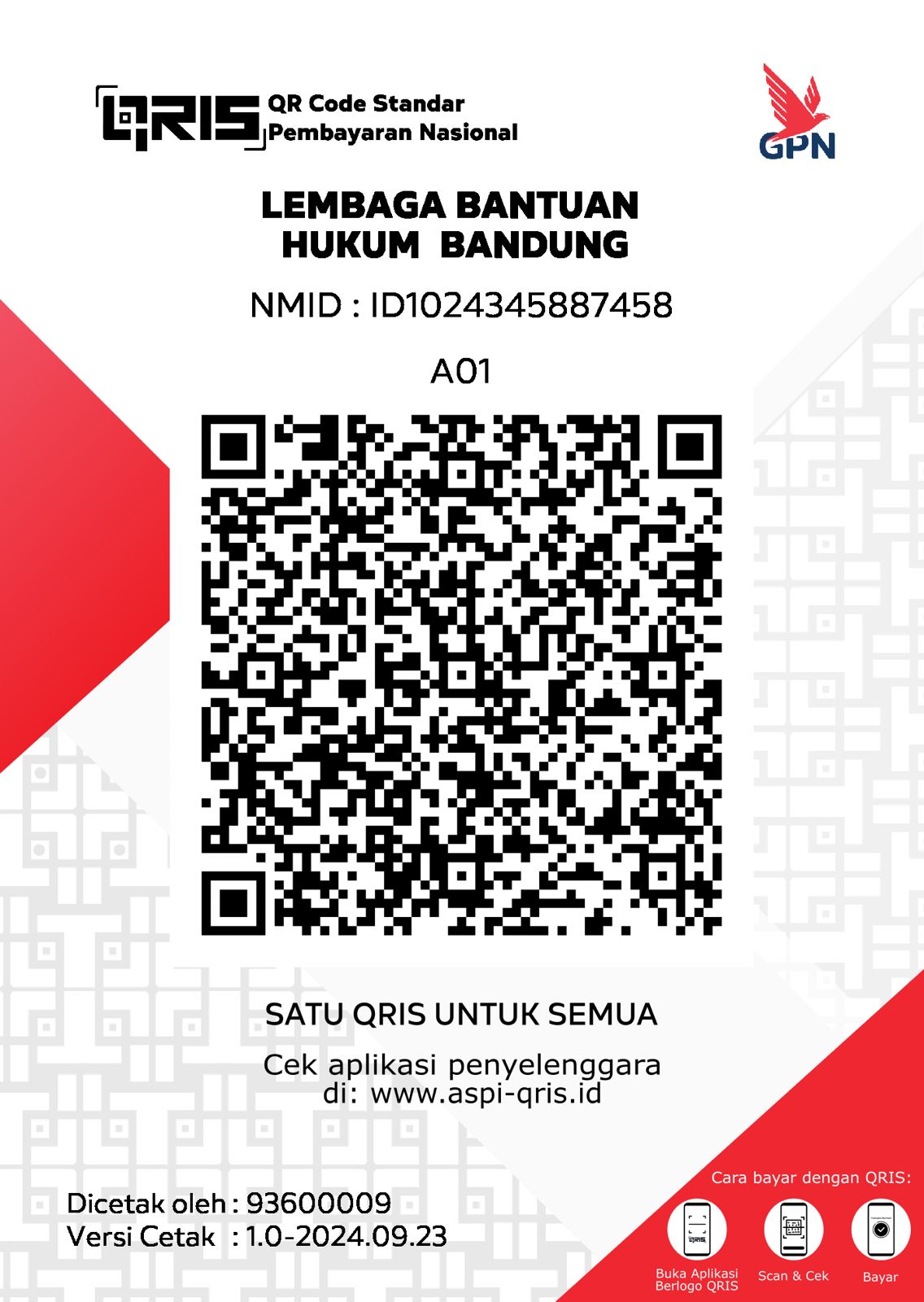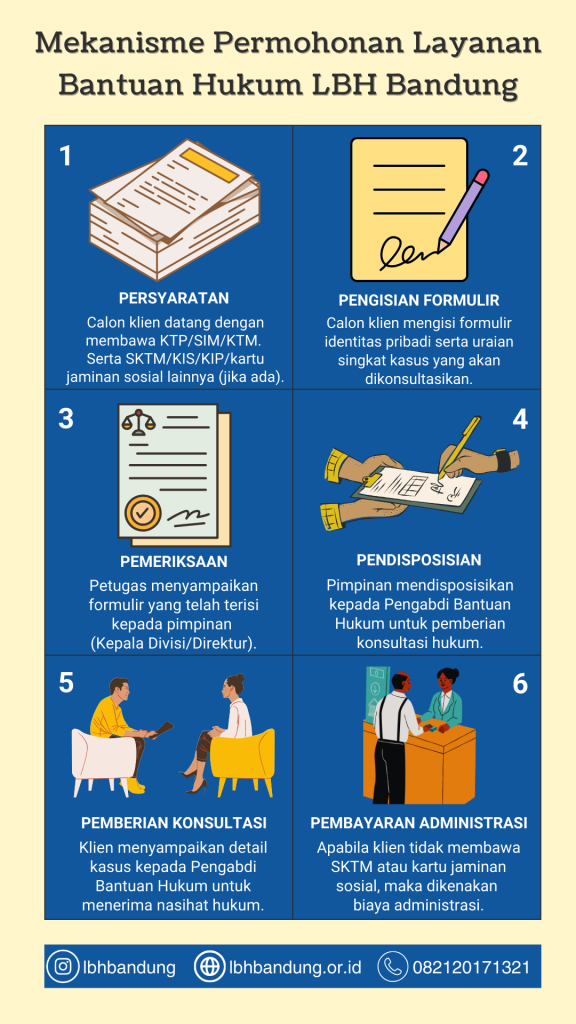

Terpenjara di tengah gurun pasir Saudi Arabia. Kisah Diana, Buruh Migran Indonesia.
Oleh Wisnu Prima. Asisten Pembela Umum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.
Rabu sore, 24 Juli 2019, sebuah pengaduan masuk ke meja Departemen Sipil dan Politik, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, kami mengendusnya sebagai kasus perdagangan manusia. Korban bernama Diana Putri (37 tahun), buruh migran perempuan asal Binjai, Sumatera Utara. Di sudut kanan bawah lembar pengaduan, tertera tanda tangan pengadu: Gumilar, dilengkapi keterangan bertuliskan “suami siri”. Saat kasus tiba di meja kami, Diana berada nun jauh di sana. Tersekap di rumah majikan, di sebuah tempat bernama As-Salmanyah, provinsi Ash–Sharqiyyah, Arab Saudi.
Sore itu juga, rapat Departemen menunjuk saya untuk menangani kasus ini. Kami sepakat, prioritas utama adalah keselamatan korban. Kami harus mencari cara agar korban dapat dipulangkan sesegera mungkin ke rumahnya. Entah bagaimana caranya.
Segeralah saya menggali informasi tambahan dari keluarga korban, dan berusaha menghubungi Diana melalui layanan WhatsApp. Seperti sudah kami duga sebelumnya, kesempatan Diana untuk berkomunikasi sangat terbatas. Pembicaraan telepon harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Melalui cara itu sedikit demi sedikit kami mengumpulkan keping demi keping informasi. Dari situlah kami berusaha menyusun keseluruhan cerita dan mempelajari duduk perkara dari kasus Diana. Berikut adalah catatan saya untuk kasus Diana.
Perjalanan ribuan kilometer dari Binjai ke Arab Saudi.
Kasus Diana bermula dari sebuah iklan lowongan kerja di luar negeri, yang diunggah pada 9 Juni 2019 di halaman Facebook milik seorang bernama Yana. Negara penempatan yang disebutkan adalah Dubai, Taiwan dan Malaysia. Gaji yang ditawarkan berkisar pada Rp. 4-6 Juta, dengan kontrak kerja rata-rata selama dua tahun; untuk pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga. Biaya pemberangkatan seluruhnya ditanggung, gratis. Si pemasang iklan, Yana, bahkan menjanjikan uang saku bagi pendaftar yang memenuhi kriteria: perempuan, sehat jasmani rohani, dan berumur 23-40 tahun.
Saat itu kondisi keuangan Diana tengah compang-camping, dan perkawinannya baru saja kandas. Tanpa banyak pikir, dia menyambar kesempatan untuk bekerja di Dubai. Melalui Facebook, Diana menghubungi Yana yang kebetulan tinggal di kota yang sama, Binjai. Saat bertemu muka langsung, Yana kembali menjelaskan tawaran kerja di luar negeri tersebut. Yana kemudian meminta keluarga Diana untuk menandatangani surat pernyataan, yang menyebutkan bahwa pihak keluarga mengizinkan Diana pergi bekerja di luar negeri.
Setelah tunai segala urusan di Binjai, Yana mengantarkan Diana menuju bandar udara internasional Kualanamu di Deli Serdang. Diana terbang sendirian, menumpang pesawat Lion Air jurusan bandar udara Soekarno Hatta (Cengkareng), Tanggerang. Sesampai di Cengkareang, dia dijemput oleh atasan Yana, seorang perempuan bernama Arsyah. Diana lalu dibawa ke sebuah villa di Bogor, untuk dikenalkan dengan Rahman, perekrut buruh migran yang bekerja untuk PT Berlian Putra Mandiri. Selanjutnya, Rahman membawa Diana ke rumah tinggalnya di Cianjur. Lalu diantarkan ke tempat penampungan. Selama dua minggu Diana tinggal di tempat penampungan tersebut, sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi.
Diana sebenarnya mendaftarkan diri untuk bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab.Tapi ternyata, Arsyah menyalurkannya ke Rahman, yang kemudian memberangkatkan Diana ke Arab Saudi. Diana juga terkejut ketika mengetahui bahwa visa yang dia miliki bukanlah visa kerja, melainkan hanya visa kunjungan 90 hari ke Arab Saudi. Lebih celaka lagi, seluruh dokumen dibuat tanpa sepengetahuannya, dan semuanya adalah dokumen palsu. Dipalsukan oleh Rahman. Sungguh seluruh proses ini melanggar pasal-pasal yang tercetak tebal di Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU Nomer 18 Tahun 2017).
Tiba-tiba saja dia memperoleh dokumen pemeriksaan kesehatan (medical check up). Diana dan keluarganya tidak pula menerima pula salinan kontrak kerja dan dokumen penempatan kerja. Surat keterangan kependudukan, juga palsu. Hanya seminggu sebelum keberangkatan, barulah Diana diberitahu bahwa dia akan ditempatkan di Arab Saudi.
Dari seluruh keterangan ini, saya membayangkan betapa luasnya jangkauan kerja jaringan pengirim manusia. Dari Binjai hingga Cengkareng dan Cianjur, sampai Arab Saudi. Lintas kota, lintas propinsi, lintas batas negara. Dalam hal rekrutmen, jaringan ini masih menggunakan cara lama.Tapi juga menyerap cara yang lebih modern, memanfaatkan teknologi internet, memasang iklan di media sosial, dan memanfaatkan fitur grup publik yang disediakan oleh Facebook. Dengan begitu mereka mampu membujuk lebih banyak calon buruh migran dengan cara cepat. Terbukti, jaringan ini mampu membujuk Diana untuk bepergian ke tempat yang jauh, ribuan kilometer dari Binjai.
Hari-hari penuh kekerasan.
Singkat cerita, Diana menginjakkan kaki di Saudi Arabia. Dia tentu tak pernah membayangkan akan bekerja di tempat yang sangat terpencil. Dari Riyadh, dia perlu menempuh perjalanan sekurang-kurangnya sejauh 475 Kilometer menuju Utara.
Pemukiman bernama As-Salmanyah itu terletak benar-benar di tengah padang gurun pasir. Dilalui jalan beraspal, tapi hanya dapat dicapai dengan kendaraan pribadi, karena sama sekali tidak dilintasi kendaraan umum.
Membaca pesan-pesan Whatsapp Diana, lagi-lagi kita mendapati kondisi kerja buruk dan tidak manusiawi. Waktu kerja dimulai pukul 03.00 waktu setempat, dan baru berakhir pada tengah malam. Sulit membayangkan, bagaimana mungkin manusia harus bekerja hingga 20-21 jam per hari. Tinggal di tengah gurun terpencil, dengan udara panas terik, dan di tengah keluarga majikan yang adat kebiasaan dan bahasanya tidak dia pahami. Lebih dari itu, Anak majikannya kerap memukul, dan majikan laki-laki melecehkannya secara seksual.

Suatu kali kami berkomunikasi, Diana sudah satu-setengah bulan dia terus menerus menjalani jam kerja yang sangat panjang. Sementara, kekerasan dan pelecehan seksual terus terjadi berulang-ulang. Seperti tahanan, dia tidak diperbolehkan meninggalkan rumah.
Dikemudian hari, Diana mendapatkan teman baru. Majikannya mempekerjakan buruh migran perempuan asal Burundi bernama Helga. Belum seminggu bekerja, Helga dipukuli dan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Diana semakin bingung, dia harus menenangkan dirinya sekaligus menenangkan Helga. Melampaui hambatan bahasa yang tak terbayangkan, keduanya menjalani hari-hari panjang yang penuh kecemasan, dengan saling saling menguatkan satu sama lain.
Seperti tahanan, Diana tidak diperbolehkan meninggalkan rumah, dan dilarang menghubungi keluarga. Selama beberapa saat, dia kehilangan kontak dari keluarga di Binjai.
Namun, kesempatan baik akhirnya datang. Beruntunglah Diana, yang berhasil menyembunyikan telepon genggamnya, agar tak jatuh ke tangan majikan. Suatu kali dia berhasil pula membobol kata sandi (password) jaringan wifi milik majikan, hingga bisa membalas pesan saya secara sembunyi-sembunyi. Dengan cara ini kami berkomunikasi dan mendiskusikan kemungkinan untuk mencari pertolongan. Dari sinilah kami mulai menempuh beberapa cara.
Mula-mula, dengan melaporkan dan meminta perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh. Namun, permintaan ditolak staf KBRI. Alasannya, KBRI tidak berwenang membawa warga negara Indonesia dari rumah warga setempat. Kalaupun hal itu bisa dilakukan, KBRI Riyad mengaku tidak mempunyai cukup sumberdaya. Selain itu, KBRI Riyadh mengeluhkan jauhnya jarak rumah majikan Diana dari Riyadh. Hal yang sungguh membuat saya kecil hati dan jengkel, KBRI Riyadh malah meminta Diana untuk bersabar, dan hendaknya memaklumi tindakan majikan. Selain itu, Diana disarankan untuk menghubungi langsung sponsor yang mengirimnya ke arab Saudi, untuk minta dijemput dan dipulangkan. Mendengar seluruh cerita ini, saya sukar mempercayai bahwa buruh migran Indonesia benar-benar dilindungi negara.

Mencari jalan pulang.
Sambil menjaga komunikasi dengan Diana, kami di LBH Bandung terus memutar otak, mencari cara untuk memulangkan korban. Berhari-hari saya mencari informasi dari berbagai arah. Termasuk mencari saran dari beberapa kawan dari berbagai latar belakang keahlian. Dari dosen hubungan internasional hingga penggiat isu buruh migran, baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang di luar negeri.
Kawan saya, pengajar di jurusan Hubungan Internasional, menasehati saya agar bersikap lebih realistis terhadap kinerja para diplomat di KBRI. Dia menyebut dua jenis diplomat, yang mestinya menjadi ujung tombak perlindungan WNI di luar negeri. Pertama adalah diplomat yang dipilih melalui proses politik, merujuk pada pejabat utama KBRI atau Duta Besar, yang selalu berupaya menjaga citra baik dirinya selama bertugas. Kedua adalah diplomat karir, yakni staf KBRI, yang sering dikritik minim inisiatif, bekerja sekedarnya, dan hanya menjalankan tugas sesuai instruksi atasan.
Seorang kawan, berpengalaman di isu buruh migran, mengatakan bahwa ada kalanya –dalam keadaan darurat- kita perlu mengevakuasi korban. Dengan kata lain, mengatur pelarian buruh migran dari rumah majikan. Pilihan ini terasa sulit bagi kami, juga Diana, mengingat dia tinggal di tengah gurun yang benar-benar terpencil dan sulit dijangkau.
Saran lain datang dari seorang penggiat Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Dia berpengalaman memulangkan buruh migran asal Indonesia. Dia menyarankan saya untuk mendesak pihak-pihak swasta yang terlibat, yakni perusahaan penyalur, perekrut lapangan dan sponsor. Mereka semua harus pula bertanggungjawab atas keselamatan buruh migran yang mereka kirimkan. Dia mengiyakan bahwa pihak KBRI memang sering tidak bekerja optimal melindungi buruh migran Indonesia.
Dari berbagai diskusi di atas, saya mencatat setidaknya ada lima jalur yang bisa ditempuhkan untuk memulangkan buruh migran yang bernasib seperti Diana.
Jalur pertama, menggunakan mekanisme pelaporan dugaan praktik perdagangan manusia ke pihak Kepolisian. Polisi akan terlebih dahulu berupaya menemukan unsur-unsur pidana perdagangan manusia, lalu berkoordinasi dengan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), lalu bekerjasama dengan pihak KBRI. Jika menempuh cara ini, kita hanya perlu menunggu Kepolisian, Kemenlu dan KBRI menunaikan tugasnya. Namun, seluruh proses membutuhkan koordinasi antar lembaga, yang sering memakan waktu panjang. Pilihan ini tidak ideal untuk Diana, yang membutuhkan pertolongan segera.
Jalur Kedua, melaporkan kasusnya ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sesudah memverifikasi laporan, Badan ini akan memanggil perusahaan penyalur tenaga kerja (PJTKI) untuk dimintai pertanggungjawabannya. PJTKI diharapkan akan berkoordinasi dengan agen di negeri penempatan. Kemudian agen di negara penempatan melakukan “mediasi” dengan majikan, agar majikan mengembalikan buruh migran ke tanah air; dengan catatan majikan setuju untuk melakukannya. Jika PJTKI mengabaikan permintaan BNP2TKI, maka ijinnya bisa dibekukan. Setelah itu BNP2TKI akan berkoordinasi dengan Kemenlu, untuk mengatur pemulangan buruh migran, melalui KBRI di negara bersangkutan. Namun, cara ini mensyaratkan kesepakatan antara KBRI dengan Kemenlu dan BNP2TKI. Sekali lagi, cara ini membutuhkan banyak waktu.
Jalur ketiga, melapor langsung kepada KBRI (Riyadh), melalui saluran hotline yang disediakan, lalu menunggu KBRI menindaklanjutinya. Cara ini mengandalkan ketersediaan sumberdaya dan kemauan KBRI. Artinya, dalam kasus ini, saya sedang setengah berjudi dengan mempertaruhkan keselamatan orang lain.
Jalur keempat, memanfaatkan portal pengaduan yang disediakan Kemenlu https://peduliwni.kemlu.go.id/pengaduan.html. Pengaduan akan diverifikasi, kemudian disalurkan ke KBRI bersangkutan. Semua keputusan akan dilaksanakan oleh KBRI. Keuntungan menempuh jalur ini, kita hanya perlu menunggu perkembangan pelaporan dari Kemenlu, dan bisa memangkas waktu. Namun, cara ini mengandalkan kesediaan Kemenlu dan KBRI untuk bertindak. Lagi-lagi, ini merupakan perjudian juga.
Jalur kelima, melakukan penjemputan non-prosedural, mengandalkan jaringan tolong-menolong di negara penempatan. Lugasnya, melarikan diri dari rumah majikan. Jalur ini bisa hemat waktu. Tetapi penjemputan (atau pelarian) harus direncanakan secara matang dan seksama. Mengeluarkan Diana dari rumah majikan, dan membawanya kembali ke kampung halaman, tentu bukan perkata kecil. Risikonya pun besar. Pihak yang membantu pelarian bisa dituduh melakukan penculikan orang dan –dalam konteks adat kebiasaan di Saudia Arabia- bisa dianggap mencuri “property” milik orang lain.
Pada akhirnya, kami harus menyiapkan berbagai opsi untuk menyelamatkan Diana. Melalui surat elektronik, kami memohon KBRI Riyadh untuk mengevakuasi korban.
Selain menempuh cara itu, kami menyiapkan diri untuk menggalang kampanye publik, menghubungi Ombudsman RI, dan berencana mendatangi kantor Kemenlu di Jakarta.
Ketika opsi-opsi tengah disiapkan, kabar baik datang dari Gumilar. Pada 30 agustus 2019, staf KBRI sudah melakukan penjemputan. Keesokan harinya, kami mendapat kabar bahwa Diana sudah berada di KBRI Riyadh. Mendengar perkembangan itu, semua opsi tambahan kami batalkan.
Sekarang menjadi jelas, apa sebab selama beberapa hari saya tidak bisa menghubungi Diana. Seorang staf KBRI Riyadh rupanya meminta Diana merahasiakan rencana pelarian dari siapapun, termasuk saya, kuasa hukumnya (saya mendapatkan kuasa dari kakak kandungnya yang tinggal di Jakarta). Jalur komunikasi Diana diputus oleh KBRI Riyadh. Diana hanya bisa menghubungi Gumilar melalui telepon genggam milik salah satu staf Kedutaan.
Bagi saya, sungguh mengecewakan bahwa KBRI Riyadh diam-diam menghalangi saya untuk memberikan bantuan hukum dan nasehat hukum, dengan tidak memberikan akses komunikasi antara saya dan Diana. Untuk alasan apapun, tindakan tersebut mengesampingkan UU Bantuan Hukum dan UU Advokat. Saya tetap tidak bisa berkomunikasi dengan Diana, hingga dia diberangkatkan ke Indonesia dan langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Binjai, pada 1 November 2019.
Hingga di sini, saya berpikir bahwa memang tidak ada mekanisme resmi untuk untuk perlindungan WNI di luar negeri, tepatnya Arab Saudi. Pelarian Diana diperlakukan sepenuhnya sebagai inisiatif perorangan, bukan tindakan resmi dari pihak negara.
Dari pengalaman menangani kasus Diana, saya menyaksikan lemahnya itikad pemerintahan dalam melawan perdagangan manusia. Indonesia tak kurang sudah menerbitkan UU No. 21 Tahun 2007 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), UU No. 18 Tahun 2017 (tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Sementara Konvensi ASEAN untuk Menentang Perdagangan Manusia sudah pula ditandatangani Presiden Joko Widodo pada pada 2015 silam. Semuanya seakan seperti humor gelap yang menertawakan nasib buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri. Dan, KBRI yang semestinya merupakan ujung tombak perlindungan WNI di luar negeri, KBRI, yang tidak mampu menerjemahkan urgensi masalah perdagangan manusia ke dalam sebuah skema perlindungan WNI yang serius.
Saya membayangkan, sudah saatnya KBRI membuka pintu seluas-luasnya untuk buruh migran yang membutuhkan pertolongan. Sudah saatnya mereka berhenti menjadi kantor yang sangat misterius serupa Batcave dan Wayne Enterprises.
Diana Kembali Berkabar.
Diana menghabiskan lima bulan yang menegangkan tanpa kepastian di luar negeri, sebelum akhirnya bisa kembali berjumpa keluarganya. Pada Jumat pagi tanggal 1 November 2019, setelah sekian lama putus kontak, dia kembali menghubungi saya. “Alhamdulilah pak, saya sudah pulang, ini sedang dalam perjalanan dengan keluarga menuju Binjai, terimakasih pak. Kondisi saat ini saya sehat pak tapi badan saya jadi kurus pak, sekali lagi terimakasih pak.” Haru sempat menyelinap masuk, hampir membongkar air mata yang disimpan dalam-dalam.
Saya kabarkan berita tak seberapa ini kepada ibu saya yang selalu bertanya mengenai perkembangan kasus Diana.
“Kumaha kabar orang Binjai teh? Iraha balikna?”
(ada kabarkah dari si orang Binjai itu? Kapan dia pulang?).
Pertanyaan itu yang sering dia lontarkan setiap kali saya pulang ke rumah. Saya selalu kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut karena saya sadar tidak ada jaminan kapan Diana akan pulang. Bahkan ketika Diana sudah berada di dalam perlindungan KBRI Riyadh sekalipun.
Pada akhirnya baru di penguhujung Jumat malam tanggal 1 November saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Esoknya saya meninggalkan Bandung. Kantor mengirim saya untuk untuk mengikuti sebuah pertemuan di Canggu, dekat Denpasar. Pertemuan ini membahas para stolen children, yakni anak-anak yang dulu dipisahkan dari keluarganya semasa Timor Leste bergejolak dalam rentan waktu 1975-1999.
Malam ini udara di Canggu terasa panas seperti biasanya. Saya tengah berada di tengah para stolen children, yang sekarang tentu bukan kanak-kanak lagi. Mereka tengah bersiap untuk menengok kembali kampung halaman dan berjumpa kembali dengan keluarganya esok hari. Minuman dan penganan tersaji di atas meja kayu besar. Haru, kantuk dan marah bercampur menjadi satu ketika mendengar cerita masa lalu mereka satu persatu. Malam ini saya memiliki kesempatan untuk menyaksikan proses panjang kepulangan sementara mereka, kembali ke ingatan masa lalunya tentang rumah setelah puluhan tahun dipisahkan.
Ditengah semua kekacauan perasaan malam ini saya teringat akan perjalanan panjang Diana menuju rumah dan seketika sebuah pesan mendarat di telepon genggam saya. Dari nomer tidak dikenal, tapi pesannya sudah kadung terbaca. “Pak, saya dapat nomor bapak dari Gumilar. Saya teman Diana selama di Cianjur, sekarang saya masih Jeddah, untung wifinya tidak dipassword”
Canggu, 11 November 2019.
*) Semua nama disamarkan.